Hari Kamis lalu, saya ketemuan sama sahabat yang emang rutin ketemuan setiap 1-2 bulan sekali, cuma untuk ngobrol dan catch-up kehidupan. Kegiatan yang saya selalu butuhkan. Lalu seperti biasa kami saling berbagi cerita, dari cerita pribadi, sampe ke kejadian-kejadian di dunia dan yah…trivia topics yang seru.
Muncullah topik jadi pemimpin. Saya bilang “Rasanya jadi pemimpin itu sebetulnya mirip sama rasa jadi wasit ya, kayaknya. Ada aja konflik dan friksi yang harus dicariin jalan tengah biar win-win solution. Artinya sistem tetap bisa jalan, tapi koneksi harus tetap terwujud.”
Dia ketawa. Ya mungkin karena emang gitu ya sebenernya hidup jadi pemimpin itu.
To be honest, saya enggak pernah membayangkan bahwa ada masa dalam hidup saya ini, ketika saya harus jadi pemimpin dan punya kompetensi mencarikan solusi. Soalnya seumur hidup saya lebih sering memberi cap diri sebagai “Sumber Malapetaka” atau “Si selalu bermasalah”. Karena emang bener sih, kenyataannya begitu. Hehehe
Yasmina si Produk Gagal
Saya selalu merasa bahwa saya ini adalah PRODUK GAGAL. Sebuah pendapat yang di validasi banyak banget pihak yang sepertinya capek menghadapi saya yang gak pernah bisa fit-in di society, berpikir dengan cara yang berbeda dengan banyak orang lainnya, ditambah enggak pernah bisa catch-up dengan pelajaran sekolah.
Saya menghukum diri saya dengan memaksakan diri agar bisa fit-in di society. Saya selalu percaya bahwa ketika saya sesuai dengan tatanan sikap di society, maka saya akan jadi manusia yang lebih baik, dan bisa dinyatakan BERHASIL.
Saya enggak memberi jeda dan napas, langsung mengubah ekstrem diri saya. Menjadi ambisius dengan jadwal padat yang saya sendiri kesulitan catch-up, sehingga enggak ngasih waktu untuk istirahat ke diri sendiri. Saya berusaha berprestasi di sekolah, meski enggak pernah merasa bahwa berprestasi versi sekolah Indonesia pada masa itu rasanya enggak penting.
Di sela-sela berupaya memahami logika pelajaran yang diajarkan dengan cara yang (kebanyakan) enggak logis itu, saya juga berusaha untuk punya teman sebanyak-banyaknya. Saya enggak pernah bisa memahami kenapa orang berprilaku seperti A, jika ada kejadian B. Tapi saya pinter sekali baca pattern dan saya bisa ngikutin pattern-nya. Padahal yang saya rasakan enggak pernah persis seperti itu.
Yah seenggaknya saya bisa menampillkan wajah yang orang-orang mau.
Saya jadi berteman dengan orang-orang yang sebenernya enggak pernah membuat saya nyaman, dan berusaha untuk tetap bisa catch-up padahal obrolannya MEMBOSANKAN sekali. Saya berusaha untuk jadi orang yang menyenangkan, dengan mendorong perasaan saya habis-habisan, dan menutupi semuanya dengan membangun image Yasmina yang asyik!
Kalau aja dulu saya ngerti bahwa tindakan menutupi diri sendiri itulah alasannya kenapa saya raging. Kenapa saya mudah sekali marah, dan menanggapi masalah seperti orang bingung. Boro- boro punya mental pemimpin, ngurus diri sendiri aja enggak bisa.
Pemimpin yang berani sayang sama dirinya sendiri
Saya baru aja menamatkan buku yang ditulis oleh Jacinda Ardern, mantan perdana menteri New Zealand. Judul bukunya “A different kind of power” dan membacanya banyak mengocok emosi saya, karena pengen sekali menyalami tangan Ibu Jacinda dan bilang “I see you..”

Manusia yang saya pimpin enggak ada 5 persen dari jumlah manusia yang dipimpin Jacinda selama 5 tahun kepemimpinannya. Tapi saya yakin, rasanya mirip. Sebab, kita terlalu sering kan mendengar bahwa menjadi pemimpin itu artinya “KUAT”. Makna kuat yang dipercaya selama ini adalah: tidak pernah nangis, enggak pernah menunjukkan emosi, seberat-beratnya kehidupan bisa tetap tersenyum, tegas, dan keras.
Sejak saya belajar soal cara kerja otak dari berbagai kelas dan buku yang ditulis para neuroscientists, saya belajar bahwa definisi kuat tersebut justru memberi gambaran pada makna mengabaikan diri sendiri. Kita akan jadi terlalu sibuk menyamakan diri dengan persepsi society sehingga lupa memikirkan diri sendiri, mengabaikan hal-hal yang seharusnya dipedulikan.
Percayalah, I’ve been there for years…..
Saya memilih Genuine Leadership
Sejak saya terapi, belajar banyak dari psikolog saya, belajar banyak soal teori dan implementasi perkembangan otak, dan menjalani berbagai proses diagnosa dari lembaga yang tersertifikasi di Belanda, saya jadi paham juga bahwa ternyata kondisi yang dulu seringkali membuat Yasmina disebut “aneh” dan “biang masalah” itu namanya ADHD, Alexithymia, Trauma, dan entahlah cap apalagi.
Sekarang sih saya udah enggak mikirin, karena sekarang rasanya sudah SANGAT NYAMAN sama diri sendiri. Meski dampaknya ketika bisa menerima diri sendiri apa adanya, bisa jadi justru perilaku yang dulunya dihindari karena tampak tidak “perform” di mata society, malah jadi lebih sering muncul. Kalo di saya, ya tentu kembali jadi Yasmina si “biang masalah” dalam versi yang jauh lebih baik.
Dulu saya pelupa banget sama apapun, habis beli barang aja bisa ketinggalan di tokonya, pulang sekolah tasnya ditinggal di kelas, sampe ke berangkat ke mol bareng temen, pulangnya sendirian, karena lupa tadi pergi sama siapa. Sekarang, saya jadi pelupa kaya gitu lagi. Tapi, karena saya ditemani proses healing-nya, jadi sekarang, saya tau cara menanganinya agar pekerjaan dan kewajiban tetap aman, tapi saya enggak rigid karena enggak mau dibilang “gak mampu” sama society.
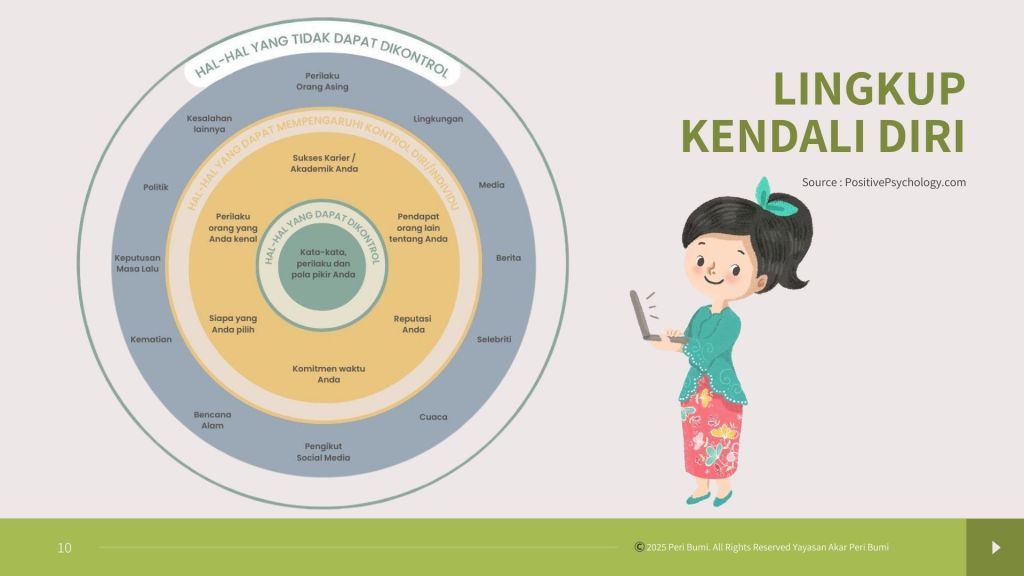
Bagusnya, sekarang saya jadi sadar, bahwa cara mikir saya yang dulu dibilang “aneh” dan “gak biasa” itu sebetulnya kemampuan saya mengintegrasikan banyak hal, membaca pattern dan memahami persoalan dari begitu banyak sudut pandang. Sehingga saya berpikir solusi diluar jangkauan berpikir orang lain. That’s actually a great thing, but hard to understand.
Maka, ketika saya akhirnya berani menerima diri saya sendiri, memberikian hak-hak esensial diri saya, maka saya menyadari bahwa saya berani jadi pemimpin, dan saya percaya bahwa menjadi pemimpin artinya harus genuine. Saya memang thin skinned, saya enggak betah diem lama, emang executive function-nya banyak kekurangan, betul. Namun, selain menerima segala hal yang selama ini di society dianggap sebagai “kekurangan” itu, saya juga menyadari bahwa dengan melakukan genuine leadership, saya bisa menciptakan ruang aman bagi banyak orang.

Saya tentu lebih memilih menciptakan ruang aman, ketimbang ketakutan. Hal yang seringkali membuat saya (tadinya) enggan jadi pemimpin adalah stigma. Iya, bahwa menjadi pemimpin yang KUAT itu artinya harus “Ditakuti”. Artinya, ya kaya kita ini kan kalau liat figur yang “lebih” daripada kita, jadinya minder, takut, segan.
Padahal kan harusnya ya jadi guru, kepala sekolah, orang tua, aparat keamanan, menteri, anggota DPR, Presiden, atau jadi pimpinan di kantor ya harusnya bikin orang merasa nyaman dan aman, kan?
Saya kan bukan setan kaya di filem-filem horror yang ketika muncul, orang2 kabur.
Pengalaman Berat di masa lalu, mengajarkan banyak hal
Saya juga percaya banget sih, ketika menjalankan kepemimpinan yang genuine, artinya saya enggak bisa kaku sama sistem, tapi harus tetap punya boundaries yang jelas. Kuncinya adalah di kemampuan meregulasi diri dan emosi. Sebab, membuat dan menjalankan sistem yang transparan adalah salah satu alat untuk membuat orang merasa aman.
Namun, ketika melaksanakan program dan kegiatan harian dengan penerapan sistem yang terlalu saklek tanpa menguatkan koneksi, akan membuat orang merasa dirantai karena dianggap mesin, bukan manusia. Jadi, sekarang saya bersyukur sekali, karena saya punya begitu banyak pengalaman di masa muda dalam menghadapi manusia.
Betul, dulu menghadapinya dengan mempelajari pattern dan masking. Namun cheat code mengenai perilaku manusia itu ada di dalam folder dalam drive di otak saya yang akhirnya jadi dictionary rapi ketika sekarang harus berhadapan dengan begitu banyak konflik dan friksi. Rasanya justru semua pengalaman yang membuat saya masking itu juga yang ngajarin saya untuk mampu beradaptasi di dunia manusia tanpa melupakan boundaries bahwa kepentingan diri sendiri saya untuk tetap sehat fisik dan mental enggak kalah penting.
Karena sekarang sudah punya rasa sayang sama diri sendiri, saya bisa menerima apapun dan mampu meregulasi diri. Ini juga makanya, dalam menerapkan genuine leadership, saya mengajak anggota tim saya untuk memulai segalanya dengan mengenal dirinya sendiri, menerima dirinya, dan mendahulukan kesehatan fisik dan mentalnya.
Being genuine is vulnerable, but that is the definition of Strong!
Berani itu bukan enggak pernah sedih, enggak pernah meltdown, selalu tegak berdiri. Berani itu artinya mau mengakui kesalahan, mau belajar dari kegagalan, dan mau minta tolong saat butuh. Genuine Leadership itu justru mulai dari kenal sama diri sendiri Tahu siapa kamu, Tahu apa yang kamu rasakan, Tahu kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan.
Leader yang rooted in SELF = leader yang bisa lift OTHERS.

Leave a comment